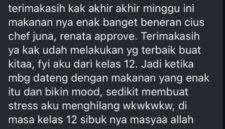Kuningan, Kontroversinews — Ramainya pemberitaan tentang sejumlah kepala daerah yang apes terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait praktik jual beli jabatan — seperti yang terjadi pada Bupati Ponorogo dan Nganjuk — kembali membuka mata publik.
Harga sebuah jabatan memang seperti asap: bisa dilihat, bisa dirasakan, tapi tak bisa digenggam. Namun, asap itu membumbung tinggi dan terlihat di mana-mana.
Persaingan untuk memperoleh jabatan begitu keras. Dari situ muncul “harga” jabatan. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan menduduki posisi strategis, hukum pasar pun berlaku — jabatan pun dijualbelikan.
Dengan tertangkapnya beberapa kepala daerah oleh KPK karena praktik jual beli jabatan, kita akhirnya menyadari bahwa meritokrasi sering kali hanya menjadi istilah manis yang sulit diwujudkan.
Yang mendapat jabatan bukanlah mereka yang paling mampu, tetapi mereka yang mau membayar. Meritokrasi pun berubah menjadi ironi.
Padahal, meritokrasi sejatinya adalah sistem yang memberikan kesempatan, jabatan, atau penghargaan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kompetensi seseorang — bukan karena faktor kekerabatan, kekayaan, atau status sosial.
Sistem ini menekankan kualifikasi, integritas, dan kinerja sebagai dasar utama dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Namun, maraknya kepala daerah yang tertangkap OTT karena jual beli jabatan menunjukkan bahwa slogan dan pelaksanaan meritokrasi masih dibayang-bayangi oleh praktik kotor dalam birokrasi.
Mungkin, hanya kepala daerah yang “kurang beruntung” saja yang tertangkap tangan oleh KPK. Sebab, dugaan kuat praktik jual beli jabatan sebenarnya terjadi di banyak tempat — hanya belum tercium.
Karena itu, para kepala daerah sebaiknya berhati-hati dalam melakukan rotasi jabatan bawahannya. Sebab, OTT oleh KPK tidak semata-mata persoalan nasib sial, tetapi juga cermin dari rusaknya sistem yang seharusnya menjunjung meritokrasi. ***